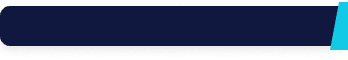10 Tahun Bencana Fukushima Membuat Nasib Energi Nuklir Suram
loading...

Kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi di Jepang membuat masa depan pembangkit listrik nuklir suram. Foto/siliconrepublic.com
A
A
A
FUKUSHIMA - Di tengah kebutuhan mendesak untuk dekarbonisasi , industri yang menyalurkan sepersepuluh listrik global harus berkonsultasi dengan publik tentang penelitian, desain, regulasi, lokasi, dan limbah reaktor .
Sepuluh tahun telah berlalu sejak bencana gempa Bumi dan tsunami merusak pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi di Jepang, memicu kecelakaan nuklir terburuk sejak bencana Chernobyl pada tahun 1986.
Kecelakaan itu terjadi pada saat harapan baru dan optimisme yang belum teruji seputar gelombang baru teknologi energi nuklir dan peran yang mungkin mereka mainkan dalam mencapai masa depan rendah karbon. Ini menyebabkan penghematan, di tengah kekhawatiran baru atas kerentanan teknologi, kelembagaan dan budaya dari infrastruktur nuklir, dan kesalahan manusia dalam merancang, mengelola dan mengoperasikan sistem yang sedemikian kompleks.
Satu dekade setelah bencana, pertanyaan-pertanyaan serius ini tetap ada, bahkan ketika krisis iklim semakin dekat. Banyak akademisi telah menganggap tenaga nuklir sebagai pilihan yang tak terhindarkan jika planet ini ingin membatasi pemanasan global. Tapi, mengingat masalah lingkungan dan sosial, orang lain lebih berhati-hati, atau tetap menentang.
Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, dalam laporan khusus tahun 2018 tentang pemanasan global, mengakui kemungkinan peran energi nuklir dalam membatasi kenaikan suhu global, tetapi menyoroti peran penting yang akan diterima publik dalam meningkatkan atau menggagalkan investasi.
Keselamatan dan biaya sering kali disorot sebagai tantangan utama industri nuklir. Teknologi baru sedang menangani masalah ini, tetapi reaktor semacam itu mungkin tidak dapat dikomersialkan sampai pertengahan abad. Kerangka waktu tersebut dapat membuat mereka ketinggalan zaman, karena persaingan teknologi seperti energi matahari dan angin (ditambah penyimpanan) menjadi semakin dominan.
Dalam pandangan kami, masalah yang lebih besar muncul: cara-cara yang buram, berpandangan ke dalam, dan tidak adil di mana sektor nuklir telah lama membuat keputusan teknologi dan kebijakan. Oleh karena itu, dua pertanyaan penting tentang masa depan energi nuklir perlu ditanyakan. Pertama, dapatkah dan akankah sektor ini mengatasi ketidaksetujuan publik? Kedua, apakah manfaatnya sepadan dengan risiko dan biaya bagi manusia dan lingkungan?
Untuk bergerak maju, industri nuklir harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini. Ini akan membutuhkan perubahan mendasar dalam pandangan - menjadi perusahaan yang lebih inklusif, akuntabel, bertanggung jawab dan berwawasan ke depan.
Awal Energi Nuklir
Pada 1950-an dan 1960-an, penyebaran energi nuklir seolah tak terbendung. Pembuat kebijakan dan pengembang berharap bahwa ini akan menjadi 'terlalu murah untuk diukur'. Tetapi tahun 1980-an dan 1990-an menyaksikan penurunan tajam dalam investasi. Meningkatnya sentimen anti-nuklir, yang dipicu oleh kecelakaan di Three Mile Island (1979) dan Chernobyl, bersama dengan kenaikan biaya konstruksi dan hilangnya subsidi pemerintah, menyebabkan periode stagnasi.
Proyeksi oleh Badan Energi Atom Internasional dari tahun 1970-an mengantisipasi bahwa tenaga nuklir akan mencapai 430 GW(e) (listrik gigawatt), atau hampir 12% dari kapasitas pembangkit listrik dunia, pada tahun 1990, dan 740–1.075 GW(e) , atau sekitar 15% dari kapasitas pembangkit listrik, pada tahun 20004. Pada kenyataannya, pada tahun 1999 hanya mencapai sekitar sepertiga dari itu, pada kapasitas 308,6 GW(e) 5. Pada akhir 1990-an, ekspektasi global akan kebangkitan kembali nuklir mulai bangkit kembali. Pada tahun 2010, konstruksi kembali meningkat.
Kemudian datanglah Fukushima. Kecelakaan tersebut dikombinasikan dengan faktor ekonomi dan politik lainnya mendorong pembubaran kompleks industri nuklir di banyak negara. Empat bulan setelah kegagalan reaktor, parlemen Jerman memilih untuk menghentikan energi nuklir seluruhnya pada tahun 2022. Kabinet Swiss mengikutinya, menyerukan penghentian lima reaktor tenaga nuklir negara itu.
Di Jepang, dari 54 reaktor yang beroperasi pada saat kecelakaan, 12 kemudian ditutup secara permanen dan 24 tetap -setidaknya untuk saat ini- ditutup.
Di Amerika Serikat, peninjauan kembali pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir dilakukan setelah Fukushima oleh Komisi Pengaturan Nuklir. Ini menimbulkan banyak masalah keamanan, tetapi negara itu tetap berkomitmen pada tenaga nuklir. Negara lain memulai kembali, atau mengambil langkah pertama mereka menuju, pembangkit energi nuklir.
Saat ini, sekitar 50 reaktor tenaga nuklir sedang dibangun di 16 negara. China memimpin, dengan 16 pabrik sedang berjalan, diikuti oleh India dan Korea Selatan. Menurut Laporan Status Industri Nuklir Dunia (WNISR), pada akhir Februari 2021, 414 reaktor tenaga nuklir beroperasi di 32 negara, menyumbang 10,3% dari pasokan listrik dunia. Secara keseluruhan, energi nuklir terus berjalan tetapi berjuang. WNISR, misalnya, menggambarkan sebagian besar industri dalam keadaan stasis.
Sementara itu, banyak yang menggambarkan energi nuklir sebagai bagian penting dari solusi perubahan iklim. Inti dari argumen ini adalah pengembangan teknologi baru. Reaktor modular kecil (SMR), misalnya, menghasilkan kurang dari 300 MW(e) per unit (cukup untuk memberi daya pada 200.000 rumah di Amerika Serikat). Ukurannya mengurangi potensi bencana sambil menstandarisasi desain dan berpotensi mengurangi biaya.
Di Amerika Serikat, segelintir SMR berpendingin air mendekati kelayakan komersial. Desain oleh NuScale, di Tigard, Oregon, menjadi yang pertama menerima evaluasi keselamatan akhir, pada tahun 2020; pabrik pertama direncanakan di Idaho pada tahun 2030. Perusahaan lain sedang mengerjakan generasi baru (Gen IV) reaktor yang lebih efisien dan lebih aman - yang sebagian besar mengandalkan pendingin selain air. Ini bahkan lebih jauh dari komersialisasi.
Keterlibatan sosial
Ini adalah perkembangan yang menarik. Tetapi sebagian besar dukungan untuk energi nuklir berfokus hampir secara eksklusif pada karakteristik tekno-ekonominya, meremehkan masalah moral dan etika yang belum terselesaikan. Para pendukung sering gagal untuk mempertimbangkan ketidaksetaraan tentang bagaimana manfaat dan risiko teknologi nuklir didistribusikan pada skala lokal, regional dan global.
Mereka juga tidak mempertimbangkan siapa yang tertinggal dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dibangun, atau siapa yang paling terpengaruh oleh masalah yang muncul.
Hampir tiga perempat dari seluruh produksi uranium secara global, misalnya, berasal dari tambang yang berada di dalam atau dekat komunitas Pribumi, misalnya di Amerika Serikat dan Australia. Tambang ini, dibiarkan tidak diremediasi setelah digunakan, telah meracuni tanah dan masyarakat, dan menjungkirbalikkan cara hidup tradisional.
Limbah nuklir juga terlibat dalam masalah keadilan, mengingat bahwa repositori jangka panjang mungkin akan ditempatkan jauh dari komunitas yang biasanya mendapat manfaat dari produksi listrik nuklir.
Industri nuklir sering menghadirkan masalah penyimpanan limbah sebagai solusi teknis yang diketahui. Realitas tentang ke mana tepatnya harus pergi, dan bagaimana, masih sangat diperdebatkan.
Sebaliknya, 'Green New Deals' yang diusulkan di beberapa negara secara eksplisit menginginkan redistribusi kekayaan, keadilan sosial dan keadilan lingkungan. Di Amerika Serikat dan negara lain di mana diskusi semacam itu muncul, dukungan publik untuk energi nuklir beragam.
Sektor nuklir secara konsisten gagal untuk terlibat secara berarti dengan publik atas keprihatinan semacam itu. Kegagalan ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 1960-an dan 1970-an. Studi psikologi risiko pada waktu itu menggambarkan publik sebagai afektif, irasional dan mengabaikan probabilitas dalam penilaian risiko, dan meminta industri nuklir untuk menerima dan merancang persepsi publik tentang risiko atau untuk mendidik publik.
Industri memilih jalur terakhir, biasanya mencoba untuk melibatkan publik hanya pada tahap akhir regulasi pabrik dan berfokus pada mendidik publik dengan pandangan industri tentang risiko. Ini adalah persamaan kuantitatif langsung yang mengalikan kemungkinan bencana dan akibatnya.
Ini sering menghindari atau mengabaikan perspektif publik. Misalnya, banyak orang bersedia menerima risiko yang disengaja atau biasa -seperti terbang, merokok, atau mengendarai mobil- terhadap risiko yang tidak biasa dan yang tidak dapat mereka kendalikan. Untuk aktivitas berisiko yang tidak disengaja, kebanyakan individu cenderung mengurangi kemungkinan dan membutuhkan tingkat keamanan dan perlindungan yang lebih tinggi untuk kenyamanan mereka.
Mode keterlibatan industri dengan publik telah menyebabkan perpecahan pakar-publik yang antagonis. Fukushima, misalnya, meninggalkan jejak yang tak terbantahkan di publik. Tetapi industri nuklir secara konsisten mengecilkan bencana dengan berfokus pada fakta bahwa hal itu tidak menimbulkan korban langsung. Meskipun tidak ada kematian manusia yang diakibatkan langsung dari kecelakaan tersebut, gangguan terhadap mata pencaharian, ikatan sosial dan kerusakan ekosistem yang tidak dapat dipulihkan menjadi signifikan.
Diperkirakan 165.000 orang mengungsi, dan, satu dekade kemudian, sekitar 43.000 penduduk tidak dapat kembali ke kota asal mereka. Penilaian risiko industri menangkap dampak ekonomi dari masalah tersebut, tetapi biasanya gagal untuk menangkap kerusakan tambahan yang lebih sulit dihitung terhadap kehidupan orang dan lingkungan.
Dari penambangan uranium hingga pengelolaan limbah, diperlukan keterlibatan warga yang tulus, yang bertujuan untuk mendengarkan, bukan meyakinkan. Baca juga: Wow, Perusahaan Induk TikTok Bytedance Mau Bikin Saingan Clubhouse?
Sepuluh tahun telah berlalu sejak bencana gempa Bumi dan tsunami merusak pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi di Jepang, memicu kecelakaan nuklir terburuk sejak bencana Chernobyl pada tahun 1986.
Kecelakaan itu terjadi pada saat harapan baru dan optimisme yang belum teruji seputar gelombang baru teknologi energi nuklir dan peran yang mungkin mereka mainkan dalam mencapai masa depan rendah karbon. Ini menyebabkan penghematan, di tengah kekhawatiran baru atas kerentanan teknologi, kelembagaan dan budaya dari infrastruktur nuklir, dan kesalahan manusia dalam merancang, mengelola dan mengoperasikan sistem yang sedemikian kompleks.
Satu dekade setelah bencana, pertanyaan-pertanyaan serius ini tetap ada, bahkan ketika krisis iklim semakin dekat. Banyak akademisi telah menganggap tenaga nuklir sebagai pilihan yang tak terhindarkan jika planet ini ingin membatasi pemanasan global. Tapi, mengingat masalah lingkungan dan sosial, orang lain lebih berhati-hati, atau tetap menentang.
Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, dalam laporan khusus tahun 2018 tentang pemanasan global, mengakui kemungkinan peran energi nuklir dalam membatasi kenaikan suhu global, tetapi menyoroti peran penting yang akan diterima publik dalam meningkatkan atau menggagalkan investasi.
Keselamatan dan biaya sering kali disorot sebagai tantangan utama industri nuklir. Teknologi baru sedang menangani masalah ini, tetapi reaktor semacam itu mungkin tidak dapat dikomersialkan sampai pertengahan abad. Kerangka waktu tersebut dapat membuat mereka ketinggalan zaman, karena persaingan teknologi seperti energi matahari dan angin (ditambah penyimpanan) menjadi semakin dominan.
Dalam pandangan kami, masalah yang lebih besar muncul: cara-cara yang buram, berpandangan ke dalam, dan tidak adil di mana sektor nuklir telah lama membuat keputusan teknologi dan kebijakan. Oleh karena itu, dua pertanyaan penting tentang masa depan energi nuklir perlu ditanyakan. Pertama, dapatkah dan akankah sektor ini mengatasi ketidaksetujuan publik? Kedua, apakah manfaatnya sepadan dengan risiko dan biaya bagi manusia dan lingkungan?
Untuk bergerak maju, industri nuklir harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini. Ini akan membutuhkan perubahan mendasar dalam pandangan - menjadi perusahaan yang lebih inklusif, akuntabel, bertanggung jawab dan berwawasan ke depan.
Awal Energi Nuklir
Pada 1950-an dan 1960-an, penyebaran energi nuklir seolah tak terbendung. Pembuat kebijakan dan pengembang berharap bahwa ini akan menjadi 'terlalu murah untuk diukur'. Tetapi tahun 1980-an dan 1990-an menyaksikan penurunan tajam dalam investasi. Meningkatnya sentimen anti-nuklir, yang dipicu oleh kecelakaan di Three Mile Island (1979) dan Chernobyl, bersama dengan kenaikan biaya konstruksi dan hilangnya subsidi pemerintah, menyebabkan periode stagnasi.
Proyeksi oleh Badan Energi Atom Internasional dari tahun 1970-an mengantisipasi bahwa tenaga nuklir akan mencapai 430 GW(e) (listrik gigawatt), atau hampir 12% dari kapasitas pembangkit listrik dunia, pada tahun 1990, dan 740–1.075 GW(e) , atau sekitar 15% dari kapasitas pembangkit listrik, pada tahun 20004. Pada kenyataannya, pada tahun 1999 hanya mencapai sekitar sepertiga dari itu, pada kapasitas 308,6 GW(e) 5. Pada akhir 1990-an, ekspektasi global akan kebangkitan kembali nuklir mulai bangkit kembali. Pada tahun 2010, konstruksi kembali meningkat.
Kemudian datanglah Fukushima. Kecelakaan tersebut dikombinasikan dengan faktor ekonomi dan politik lainnya mendorong pembubaran kompleks industri nuklir di banyak negara. Empat bulan setelah kegagalan reaktor, parlemen Jerman memilih untuk menghentikan energi nuklir seluruhnya pada tahun 2022. Kabinet Swiss mengikutinya, menyerukan penghentian lima reaktor tenaga nuklir negara itu.
Di Jepang, dari 54 reaktor yang beroperasi pada saat kecelakaan, 12 kemudian ditutup secara permanen dan 24 tetap -setidaknya untuk saat ini- ditutup.
Di Amerika Serikat, peninjauan kembali pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir dilakukan setelah Fukushima oleh Komisi Pengaturan Nuklir. Ini menimbulkan banyak masalah keamanan, tetapi negara itu tetap berkomitmen pada tenaga nuklir. Negara lain memulai kembali, atau mengambil langkah pertama mereka menuju, pembangkit energi nuklir.
Saat ini, sekitar 50 reaktor tenaga nuklir sedang dibangun di 16 negara. China memimpin, dengan 16 pabrik sedang berjalan, diikuti oleh India dan Korea Selatan. Menurut Laporan Status Industri Nuklir Dunia (WNISR), pada akhir Februari 2021, 414 reaktor tenaga nuklir beroperasi di 32 negara, menyumbang 10,3% dari pasokan listrik dunia. Secara keseluruhan, energi nuklir terus berjalan tetapi berjuang. WNISR, misalnya, menggambarkan sebagian besar industri dalam keadaan stasis.
Sementara itu, banyak yang menggambarkan energi nuklir sebagai bagian penting dari solusi perubahan iklim. Inti dari argumen ini adalah pengembangan teknologi baru. Reaktor modular kecil (SMR), misalnya, menghasilkan kurang dari 300 MW(e) per unit (cukup untuk memberi daya pada 200.000 rumah di Amerika Serikat). Ukurannya mengurangi potensi bencana sambil menstandarisasi desain dan berpotensi mengurangi biaya.
Di Amerika Serikat, segelintir SMR berpendingin air mendekati kelayakan komersial. Desain oleh NuScale, di Tigard, Oregon, menjadi yang pertama menerima evaluasi keselamatan akhir, pada tahun 2020; pabrik pertama direncanakan di Idaho pada tahun 2030. Perusahaan lain sedang mengerjakan generasi baru (Gen IV) reaktor yang lebih efisien dan lebih aman - yang sebagian besar mengandalkan pendingin selain air. Ini bahkan lebih jauh dari komersialisasi.
Keterlibatan sosial
Ini adalah perkembangan yang menarik. Tetapi sebagian besar dukungan untuk energi nuklir berfokus hampir secara eksklusif pada karakteristik tekno-ekonominya, meremehkan masalah moral dan etika yang belum terselesaikan. Para pendukung sering gagal untuk mempertimbangkan ketidaksetaraan tentang bagaimana manfaat dan risiko teknologi nuklir didistribusikan pada skala lokal, regional dan global.
Mereka juga tidak mempertimbangkan siapa yang tertinggal dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dibangun, atau siapa yang paling terpengaruh oleh masalah yang muncul.
Hampir tiga perempat dari seluruh produksi uranium secara global, misalnya, berasal dari tambang yang berada di dalam atau dekat komunitas Pribumi, misalnya di Amerika Serikat dan Australia. Tambang ini, dibiarkan tidak diremediasi setelah digunakan, telah meracuni tanah dan masyarakat, dan menjungkirbalikkan cara hidup tradisional.
Limbah nuklir juga terlibat dalam masalah keadilan, mengingat bahwa repositori jangka panjang mungkin akan ditempatkan jauh dari komunitas yang biasanya mendapat manfaat dari produksi listrik nuklir.
Industri nuklir sering menghadirkan masalah penyimpanan limbah sebagai solusi teknis yang diketahui. Realitas tentang ke mana tepatnya harus pergi, dan bagaimana, masih sangat diperdebatkan.
Sebaliknya, 'Green New Deals' yang diusulkan di beberapa negara secara eksplisit menginginkan redistribusi kekayaan, keadilan sosial dan keadilan lingkungan. Di Amerika Serikat dan negara lain di mana diskusi semacam itu muncul, dukungan publik untuk energi nuklir beragam.
Sektor nuklir secara konsisten gagal untuk terlibat secara berarti dengan publik atas keprihatinan semacam itu. Kegagalan ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 1960-an dan 1970-an. Studi psikologi risiko pada waktu itu menggambarkan publik sebagai afektif, irasional dan mengabaikan probabilitas dalam penilaian risiko, dan meminta industri nuklir untuk menerima dan merancang persepsi publik tentang risiko atau untuk mendidik publik.
Industri memilih jalur terakhir, biasanya mencoba untuk melibatkan publik hanya pada tahap akhir regulasi pabrik dan berfokus pada mendidik publik dengan pandangan industri tentang risiko. Ini adalah persamaan kuantitatif langsung yang mengalikan kemungkinan bencana dan akibatnya.
Ini sering menghindari atau mengabaikan perspektif publik. Misalnya, banyak orang bersedia menerima risiko yang disengaja atau biasa -seperti terbang, merokok, atau mengendarai mobil- terhadap risiko yang tidak biasa dan yang tidak dapat mereka kendalikan. Untuk aktivitas berisiko yang tidak disengaja, kebanyakan individu cenderung mengurangi kemungkinan dan membutuhkan tingkat keamanan dan perlindungan yang lebih tinggi untuk kenyamanan mereka.
Mode keterlibatan industri dengan publik telah menyebabkan perpecahan pakar-publik yang antagonis. Fukushima, misalnya, meninggalkan jejak yang tak terbantahkan di publik. Tetapi industri nuklir secara konsisten mengecilkan bencana dengan berfokus pada fakta bahwa hal itu tidak menimbulkan korban langsung. Meskipun tidak ada kematian manusia yang diakibatkan langsung dari kecelakaan tersebut, gangguan terhadap mata pencaharian, ikatan sosial dan kerusakan ekosistem yang tidak dapat dipulihkan menjadi signifikan.
Diperkirakan 165.000 orang mengungsi, dan, satu dekade kemudian, sekitar 43.000 penduduk tidak dapat kembali ke kota asal mereka. Penilaian risiko industri menangkap dampak ekonomi dari masalah tersebut, tetapi biasanya gagal untuk menangkap kerusakan tambahan yang lebih sulit dihitung terhadap kehidupan orang dan lingkungan.
Dari penambangan uranium hingga pengelolaan limbah, diperlukan keterlibatan warga yang tulus, yang bertujuan untuk mendengarkan, bukan meyakinkan. Baca juga: Wow, Perusahaan Induk TikTok Bytedance Mau Bikin Saingan Clubhouse?
(iqb)